Tujuh Hari Menuju Surga
Cerpen MH Poetra (Republika, 7 Maret 2010)

RABU, 31 Desember 2006 (AKSARA News)
Telah ditemukan mayat laki-laki dengan kondisi mengenaskan di kedai tuak Marpaung seputar wilayah Halat, Kec. Medan Area Selatan, Medan, Sumatra Utara. Petugas kepolisian yang memeriksa korban tidak menemukan kartu identitasnya. Hanya ada sebuah notes kecil berisi catatan-catatan harian, pensil pendek, bungkus kretek, pemantik, dan beberapa remukan kertas. Korban akan dibawa ke Laboratorium Forensik Medan, guna diautopsi.
***
Mata kami masih saling bertatap, dingin. Kalau kau pernah ke Alaska dan merasakan betapa bekunya suasana di sana, begitulah sekarang hawa di ruangan kedai tuak ini. Tapi, tatapan mata mereka seperti api, panas, membakar segala. Udara hangus, bertuba oleh kata-kata maki yang terdengar samar. Dan, kami semakin dekat.
***
24 Desember 2006, Rantauprapat
Aku hidup dan besar dari garis yang dijalin oleh misteri. Begitulah, aku memaknai hidup tidak dari apa yang diajarkan oleh ibu dan bapakku, bahkan aku tidak tahu siapa mereka. Jalan hidupku hanya berujung pada kata: resah, dan sunyi. Harapan sunyi akan ketakutan yang mabuk, serta kegilaan yang kuat bagiku adalah hal yang biasa.
Di kota asalku, Rantauprapat—sebuah kota dengan panorama kumuh, jauh dari apa yang dibayangkan orang tentang kota besar, banyak orang-orang gila karena ketakutan; semisal kegagalan atau kecemasan karena profesi yang tak kunjung membaik, bahkan sekadar risau lantaran pasangan yang tak lagi memuaskan. Aku tertawa kecil. Bagiku, sungguh, ketidaktakutanku itulah yang paling menakutkan.
Lalu, bagaimana denganmu, Kawan?
***
Maut adalah kekalahan hidup. Luka sebagai penghantarnya. Tuak tak lagi memikat, walau begitu, segera kuhabiskan saja sisanya yang masih membusa di meja, sebelum nanti aku tak lagi sempat menikmatinya. Sekecil apa pun itu, pantang bagiku menyisakan sesuatu.
Kau tahu, kami sudah sama terbakar dari api mata masing-masing. Tinggal dalam hitungan detik, pecahlah apa yang dinama kesunyian.
***
25 Desember 2006, Rantauprapat
Bohong besar jika aku bilang tidak suka tuak atau bir. Meski agamaku melarangnya. Sudahlah. Ini Hari Natal, aku akan berkunjung ke rumah kawan-kawanku yang merayakannya. Sekadar bertegur sapa, basa-basi, aku bisa pulang dengan enteng, seolah baru kembali dari surga karena dahaga yang candu terpuaskan. Bagi mereka, itu keharusan turun-temurun, seperti ritual sakral yang meluruhkan penat raga di tahun sebelumnya. Ini akan terus berulang sampai tujuh hari ke depan. Kenikmatan yang cukup panjang kukira, setidaknya, dapat mencairkan batu-batu es yang memenuhi rongga kepalaku. Ah, aku tidak mau terlalu larut karena besok harus ke Kota Medan, kota sumber mata pencaharianku, meski hanya sebagai penjaja suara melalui sajak-sajakku di tempat-tempat umum. Jangan kira aku sengsara. Aku cukup puas, karena terbebas dari keterikatan atau ketergantungan dari sesuatu—apa pun itu. Aku akan menemui perempuanku di Lubuk Pakam. Ini penghujung tahun, seperti tahun-tahun sebelumnya, bersua dengannya adalah sebuah keharusan.
Sebab perempuan, bagiku, adalah candu segala candu. Hutan yang mengharuskan aku tersesat di dalamnya.
***
26 Desember 2006, Rantauprapat-Medan
“Tuhan menangis di luar,
Ditambah laju, kereta menggigil badan.
Sekeliling diam. Masing di kepala menampar-nampar
Ditambah lagi kenang yang mengapit kelok jalan.’’
-Lelap hingga tuju-
***
Mereka—ke empat orang itu— setelah kemabukan yang entah telah mencapai tahap apa, tiba di hadapanku seolah menjadi iblis-iblis bengis yang siap melumatku mentah-mentah. Tapi, hey! Aku adalah macan, dengan taring dan cakar yang bisa melumpuhkan apa saja. Lelaki gemuk dengan kaus oblong putih itu langsung memukul pelipisku dengan membabi buta.
***
27 Desember 2006, Medan
Malam ini, Medan sangat lengang. Ketika berjalan, angin yang mengabarkan dingin menyertai tiap langkahku. Kadang, aku ingin menjelma sebagai macan; punya taring, punya cakar, punya mata yang membius, dan aku akan jadi penguasa dunia. Dengan taringku, aku akan mencabik teka-teki yang lebih dulu telah ditanam dalam kepala pascakelahiranku; aku akan mengoyak-ngoyak bulan dengan keirian karena keindahannya yang dijadikan kiblat oleh para pencinta sebagai mutiara jiwa yang haus. Dan mataku, ini mataku, aku tidak lagi tahu untuk apa sejatinya mataku ini.
“Jadi kambing di kampung sendiri, tapi jadi banteng di kampung orang,” kata orang-orang di kampungku.
***
Aku terjerembab. Belum sempat bangkit melawan, lelaki kurus dengan muka yang masih lebam itu turut memukulku, gelas di tangannya langsung dihantamkan tepat di jidatku. Seketika suasana riuh. Pemilik kedai berteriak mencak-mencak, ingin segera mengakhiri pertikaian. Darahku bercucuran.
Tapi, iblis-iblis ini terus saja menjejaliku dengan pukulan mematikan.
***
28 Desember 2006, Medan
“Luka bersama mana yang kita cari,
Hidup jauh sudah mengemudi sepi.”
-Lee-
Mengasingkan diri setiap malam di sebuah lorong yang becek, gelap, dan sempit, ditemani kertas usang dan pensil berukuran 3 cm yang tumpul luar biasa, serta ide-ide yang berhamburan di kepala, bukanlah kemauanku. Tikus-tikus begitu setia menemaniku, satu berbadan besar hitam sedang sibuk sendiri di sudut lorong mengais-ngais kantongan plastik. Di tepi got, tikus berbadan kecil dengan mata tirus dan ekor yang lumayan panjang sedang menoleh ke kananke kiri. Jangan-jangan resahku telah merasuk ke dalam resahnya.
Di lorong ini aku kerap meniduri langit dengan kegelapan.
Dan sepi adalah kegagalan diri. Nasib kesendirian yang mengadu.
***
Tubuhku tak bisa digerakkan lagi, tapi mataku masih awas. Mereka masih saja menjadikan tubuhku sebagai ladang pembantaian. Aku melihat orang-orang begitu ketakutan, seolah sedang disuguhi tontonan pembantaian kejam di masa-masa lalu, seperti PKI atau Nazi. Tapi, ini lebih jauh mengerikan. Mengapa mereka diam saja? Tidakkah ada rasa iba untuk menolongku? Ah, kiranya baru kutersadar, ketakutan kerap menjadikan kita sebagai budak, di mana tubuh dan pikir tak lagi kita yang menentukan.
Di mana Maya?
***
29 Desember 2006, Lubuk Pakam
Maya Marsita namanya, perempuan dengan tubuh semesta dan berambut langit itu, entah kenapa malam ini ia datang terlambat, biasanya ia tak pernah membuatku lama menunggu. Beberapa orang di stasiun pun hanya menggeleng memberi tahu, bahwa mereka tak tahu, atau tak peduli. Perlahan sayup terdengar suaranya. Teriakan, jeritan, dan makian yang keluar dari mulutnya, makin lama terdengar makin menyiksa. Kuburu arah suara itu. Di sudut peron yang sunyi, seorang lelaki kurus tinggi berkulit legam dan berkacamata, tampak sedang menarik tangannya dengan paksa. Jeritan Maya semakin menjadi begitu dilihatnya aku berdiri di sana. Sekonyong-konyong kulayangkan tinjuku ke arah wajah lelaki itu tanpa henti. Ternyata, sudah banyak orang yang menonton kejadian itu. Maya berdiri menggigil tak jauh dariku, wajahnya pucat.
Kulihat lelaki tadi berlumuran darah, tak bergerak sama sekali, napasnya tersengal. Beberapa orang yang menonton pun hanya terpaku diam.
Seseorang berkata dengan nanar, “Lelaki itu anggota geng dari sekumpulan lelaki tua, jagoan stasiun ini. Siapa pun yang berani menyentuh salah satu di antara mereka, pasti akan mati, akan dicari sampai ketemu, lalu dibunuh.’’
Seorang lagi menyarankan agar aku segera meninggalkan kota ini, karena tak ada jaminan bisa menyembunyikan diri.
Aku menyalakan kretek, menghisapnya dalam-dalam, lalu kugapai tangan Maya dan menuntunnya menjauh dari kerumunan orang. Ia mengikutiku dengan patuh, bahkan sambil menyandarkan kepalanya ke pundakku. Kami berjalan semakin jauh, tak peduli tatapan ganjil orang-orang.
Ini hidupku! Dalam hati aku bergumam pada mereka, “Ah kalian, kayak tak tahu aku saja. Seribu setan saja akan tunduk padaku!”
***
Kematiankah begitu dingin? Aku tak tahu. Jangan-jangan iblis-iblis ini tidak paham betapa pentingnya satu nyawa. Setengah sadar, aku lihat lelaki kurus berwajah lebam itu menarik belati dari pinggangnya. Tanpa ragu ia tancapkan tepat di dadaku. Dan, oh!
Aku berteriak sekencang mungkin, “Biar tertanam seribu belati di tubuhku, tahukah kalian, bukan kematianku yang menghentikan segalanya!”
Tusukan-tusukan dan hantaman-hantaman itu tak henti juga menetaki tubuhku. Lantai menjadi lautan darah. Pandanganku mengabur.
“Duka maha-Mu lebih tinggi-hilang bayang meniba tara untuk-Mu lagi-pulang kenang.”
Lalu, kulihat samar wajah-wajah mereka yang tertawa puas.
***
30 Desember 2006, Kedai Tuak, Pinggiran Kota Medan
“Hidup adalah kesiaan masing ruh,
Ajal dan waktu, hanya pembatas keluh.”
Aku duduk di antara lelaki-lelaki tua itu. Sebegitu asyiknya seolah tak ada beban hidup yang bergelayut di benak mereka. Aku juga tidak tahu apakah mereka hidup sendiri sepertiku, atau ada anak-istri yang sebenarnya menanti mereka dengan penuh kecemasan dan harapan di rumah. Mereka sedang bergitar ria, menyanyi riuh tak jelas. Seorang lelaki gemuk memakai kaus oblong putih dengan janggut dan kumis yang tak terurus, paling keras suaranya. Dan, satu suara terdengar sedikit merdu—meski masih fals di telingaku—itu suara seorang lelaki berbadan kurus tinggi berkulit legam dengan wajah yang masih terlihat lebam.
Dan, oh, dia …
Dia tidak asing lagi di mataku. Dia lelaki yang kemarin malam menarik paksa tangan Maya. Aku tak peduli sorot mata lelaki itu, juga sorot mata anak-anak buahnya yang rata-rata berbadan kekar itu. Pun tak kuhiraukan sama sekali apa maunya mereka. Tuhan saja kadang terlupa ketika aku asyik menenggak tuak. Yang jelas, tuak di gelas yang tinggal setengah kutenggak habis sekali teguk.
***
31 Desember 2006, (kosong)
***
(Maya Marsita)
01 Januari 2007
Aku masih menantimu, Lee, kenapa belum juga datang? Padahal, kau berjanji akan menemaniku menikmati malam Tahun Baru. Aku ingin jelaskan padamu, lelaki yang menarik tanganku itu sebenarnya abangku sendiri. Ia tidak suka aku menjadi wanita panggilan. Aku menyesal karena tak sempat mengatakannya padamu, Lee.
Setelah kejadian malam itu, sehabis mengantarku, kau langsung pergi. Saat kutanya hendak ke mana, kau hanya menjawab singkat. “Mau ke surga!” katamu.
***
Jakarta, Februari 2010
MH Poetra, lahir di Medan, 28 Oktober 1988.
Saat ini bergiat di LEKAS dan Komunitas Mata Aksara.
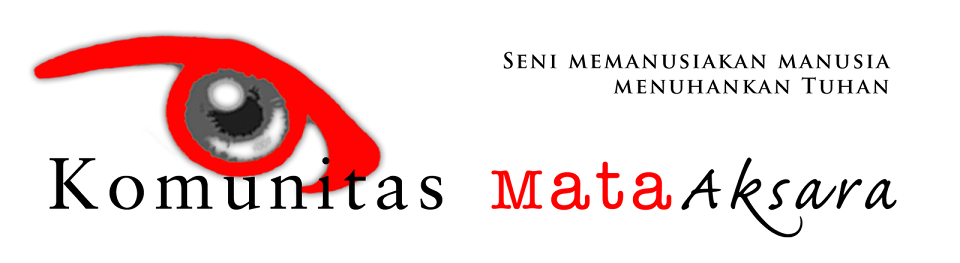
i like this very much..
BalasHapus