Perempuan Indonesia di Labirin Sastra dan Budaya
Oleh: Handoko F. Zainsam
“MEMANUSIAKAN MANUSIA.” Mungkin itulah kalimat awal yang cukup tegas untuk memberikan dan mengukuhkan keberadaan atau eksistensi tiap manusia. Bukan tanpa akar, jauh putik sebelum kembang, di perjalanan eksistensinya, banyak terjadi silang-sengkarut dominasi segala kegiatan atau aktivitas suatu golongan terhadap golongan lain. Silang-sengkarut ini muncul lantaran terjadinya pembagian fungsi yang akhirnya menutup terjadinya double function (dengan berbagai fungsi) atau change position (peluang untuk menempati fungsi lain).
Dalam perjalanan sejarah pemikiran barat, postrukturalismelah yang harus diakui memiliki sumbangan terpenting terhadap kebudayaan--dalam hal ini gerakan feminisme; seiring dengan pergeseran paradigma dari pusat ke pinggiran. Lantas studi kultural selanjutnya diarahkan pada kompetensi masyarakat yang terpinggirkan atau masyarakat marjinal. John Stuart Mill dan Harriet Taylor, yang dikutip Tong dalam “Feminist Thought: Pengantar paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis (1998:23) menyatakan bahwa muncul teori feminis berlatar atas bangkitnya kesadaran bahwa perempuan sebagai manusia juga selayaknya memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki. Untuk menempuh totalitasnya (kebahagiaan/kenikmatan) yakni dengan membiarkan setiap individu mengejar apa yang mereka inginkan, selama mereka tidak saling membatasi atau menghalangi di dalam proses pencapaian tersebut.
Di posisi inilah, feminisme lahir. Hal ini akibat dari kuatnya hegemoni kekuasaan laki-laki yang mengaburkan atau mengerdilkan peran perempuan untuk memiliki fungsi lain. Tapi, apakah itu sebuah pengerdilan atau sebenarnya adalah sebuah pembagian peran? Permasalahan menjadi lebih rumit dan akhirnya menjadi sebuah ‘kefatalan’ ketika ditutupnya peran lain yang sebenarnya bisa dilakukan oleh perempuan. Gerakan femininis pun mewabah. Lantas, bagaimana Indonesia?
Kebudayaan dan Kekuatan Perempuan
MENELISIK SEJARAH peradaban dan masyarakat (kebudayaan) masa lalu. Perempuan Indonesia ‘sepertinya’ tercitrakan dalam suatu kontruksi pemikiran bahwa perempuan sebagai ‘wong njero’ (orang dalam) sedangkan laki-laki sebagai ‘wong njaba’ (orang luar). Apakah benar begitu?
Dalam beberapa kitab lama, baik di Serat Pararaton, Babad Tanah Jawa, serat Centhini, Kaba Cindua Mato hingga teks-teks sastra kekinian sepertinya ‘tidak seratus persen benar’ bahwa perempuan menjadi terpinggirkan—hanya sekedar menjadi kepuasan nafsu berahi kaum lelaki.
Dalam perjalanan karya sastra lama, perempuan memiliki peran yang cukup baik di tataran ekonomi, sosial, politik, dan seni. Munculnya Ratu Sima atau Tribuana Tungga Dewi mengukuhkan keberadaan perempuan di kancah kekuasaan. Di ranah Minangkabau dikenal adanya Bundo Kanduang yang konon diciptakan bersamaan dengan alam semesta ini (samo tajadi jo alamko) dalam kaba Cindua Mato. Dalam hikayat tersebut, peran perempuan penjadi sentral dan memegang kekuasaan penuh di banding laki-laki.
Hal ini memang berseberangan dengan kebudayaan yang berkembang di wilayah Barat. Kebudayaan barat cenderung maskulin (patrilineal) dan kebudayaan timur cenderung feminin (matrilineal). Hal ini dapat diketahui dari konstruksi mitos-mitos yang berkembang kedua wilayah tersebut.
Di dunia Timur, konstruksi pemikiran tentang perempuan sebagai individu yang menempati urutan pertama dalam kiblat religiusitas semakin kuat terkukuhkan. Perempuan menjadi ibu keyakinan dan pengetahuan. Sebagai contoh adalah mitos atau keyakinan yang berkembang di negara-negara timur seperti Jepang dan Cina. Demikian pula Indonesia. Di Cina mengenal Dewi tentinggi Kwan Im--Avalokitesvara Bodhisattva (Dewi kebijaksanaan), Di Jepang ada Amatersu-ōmikami (Dewi Matahari), dan di Indonesia mengenal Ratu Pantai Selatan (penguasa tunggal laut dan samudra). Perempuan sebagai kiblat spiritual semakin kentara dengan menempatkan urutan pertama dan kedua sebagai sosok yang harus di hormati. Sementara laki-laki menempati urutan ketiga. Hal ini jauh berbeda dengan konstruksi pemikiran di dunia barat yang menjadikan kaum laki-laki lebih dominan.
Sastra dan Elan Vital Feminisme
KARYA SASTRA lahir dari suatu masyarakat. Karya sastra ditulis untuk menjadi ‘potret’ suatu masyarakat dalam kerangka tertentu, suatu dunia luar. Dari landasan inilah layaknya karya sastra ditangkap sebagai gambaran sebuah gejala sosial dan budaya yang terdokumentasikan.
Dalam ranah kesusastraan memang perlu kembali diselaraskan akan arus gerak feminisme ini. Saya melihat posisi atau kedudukan feminisme dalam kesusastraan di dua tataran. Pertama, sastra yang membahas tentang perempuan. Kedua, perempuan sebagai pencipta karya (peran penulis perempuan).
Pada tataran pertama, Sastra yang membahas perempuan—perlu adanya kesepahaman mengenai karya sastra dan tafsirnya. Mengambil pendapat Nyoman Kutha Ratna dalam Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta (2005:16) Karya sastra merupakan rekonstruksi yang harus dipahami dengan memanfaatkan mediasi. Karya sastra membangun dunia melalui energi kata-kata. Melalui kualitas hubungan paradigmatik, sistem tanda, dan sistem simbol, kata-kata menunjuk sesuatu yang lain di luar dirinya.
Perlu disadari bahwa sastra pada hakikatnya adalah sebuah imajinasi dan kreativitas. Sehingga acuan dalam sastra adalah dunia fiksi atau imajinasi. Tak bisa dipungkiri bahwa sastra adalah sebuah tranformasi kenyataan ke dalam teks. Sastra menyajikan dunia dalam kata, yang bukan dunia sesungguhnya, namun sebuah dunia yang ‘mungkin’ada. Walaupun berbicara dengan acuan dunia fiksi, namun, menurut Max Eastman, kebenaran dalam karya sastra sama dengan kebenaran di luar karya sastra, yaitu pengetahuan sistematis yang dapat dibuktikan. Fungsi utama sastrawan adalah membuat manusia melihat apa yang sehari-hari ada di dalam kehidupan, dan membayangkan apa yang secara konseptual dan nyata sebenarnya sudah diketahui (Welleck & Warren, 1990 : 30-31).
Sebagai dunia rekaan, sastra tentu memiliki sebuah kegunaan; salah satu diantaranya sebagai sebuah pelepasan hasrat estetika (happiness) dan manfaat (usable). Karya sastra menjadi suatu hal yang menyenangkan, estetis, dan perseptif. Selain itu sastra juga memiliki fungsi katarsis, yaitu membebaskan pembaca dan penulisnya dari tekanan emosi. Mengekspresikan emosi berarti melepaskan diri dari emosi itu, sehingga terciptalah rasa lepas dan ketenangan pikiran (Welleck & Warren, 1990 : 34-35).
Fungsi yang sama pun juga diemban oleh kebudayaan—seluruh aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, yang diperoleh dengan cara belajar, termasuk pikiran dan tingkah laku. Sedangkan hakikat sastra dan kebudayaan adalah hakikat fiksi dan fakta. Karya sastra dibangun atas dasar rekaan, dienergisasikan oleh imajinasi, sehingga dapat memuat kenyataan-kenyataan. Sedangkan kebudayaan memberi isi, sehingga kenyataan yang ada dalam karya sastra dapat dipahami secara komprehensif.
Dalam perkembangan disiplin ilmu pegetahuan muncul istilah cultural studies. Dalam ranah ini sastra menjadi salah satu kajian pembentuk atau padanan dari sebuah kenyataan (mirroring). Sastra juga bisa disikapi sebagai rekaman peristiwa-peristiwa kebudayaan.
Perlu dipahami pula bahwa karya sastra memiliki tafsir yang sangat terbuka. Hal ini tergantung pada situasi dan kondisi pembacanya (pengetahuan dan perasaan apa yang ada dipikiran pembacanya). Karya sastra memiliki ruang-ruang kosong, tempat para pembaca memberikan penafsirannya. Sedangkan makna suatu karya sastra dapat berubah-ubah tergantung pada ‘pengetahuan dan perasaan’ pembacanya.
Perlu dipahamai pula bahwa sastra lahir berdasarkan atau memiliki keterkaitan dengan jaman penulisannya (kontekstual). Selain itu karya sastra juga sarat dengan intersubjektif. Artinya, teks tergantung pada bagaimana penafsiran-penafsiran yang diajukan orang lain dalam kode-kode dan konvensi-konvensi suatu komunitas, dan dengan demikian disahkan atau ditolak (Cavallaro, 2001 : 110-111).
Pendapat ini terkukuhkan dengan menyarikan pendapat Julia Kristeva dan Roland Barthes yang menyatakan bahwa teks dibentuk oleh kode-kode dan konvensi-konvensi budaya serta mewujudkan ideologi tertentu. Sementara Antonio Gramci mengidentifikasikan mekanisme-mekanisme yang memungkinkan sebuah sistem dalam mempertahankan kekuasaannya menjadi akar konsep hegemoni. Hegemoni berkembang dengan meyakinkan kelompok-kelompok sosial yang subordinat agar menerima sistem kultural dan nilai-nilai etik yang dihargai oleh kelompok yang berkuasa seolah-olah sistem dan nilai tersebut benar secara universal dan melekat dalam kehidupan manusia.
Dalam karya sastra banyak sekali penggambaran posisi, peran, dan fungsi perempuan di dalam masyarakat dan budaya—seperti yang telah di kemukakan di atas.
Mengenai penulis perempuan saya teringat kalimat Prof. Dr Soenarjati Djajanegara dalam bukunya Kritik Sastra feminis yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Seni dan Budaya Fakultas Sastra Universitas Indonesia di Depok mengenai pengarang. Soenarjati mengatakan bahwa belum tentu penulis perempuan akan menghasilkan karya sastra yang membela perempuan, begitu juga sebaliknya, tidak semua penulis laki-laki pasti tidak berpihak pada perempuan.
Soenarjati berkesimpulan, paling tidak ada beberapa landasan yang bisa digunakan dalam kritik sastra dengan perspektif feminisme. Pertama, kelompok feminis yang berusaha menjadi kritikus sastra dengan melihat ideologinya. Mereka ini umumnya akan menyoroti persoalan stereotip perempuan. Kedua, genokritik yang mencari jawaban apakah penulis perempuan itu merupakan kelompok khusus sehingga tulisannya bisa dibedakan dengan penulis laki-laki. Ketiga, kelompok feminis yang menggunakan konsep sosialis dan marxis. Runutan pemikirannya yang terbangun dengan menelisik kenyataan bahwa perempuan tidak memiliki dukungan penuh alat-alat produksi yang bisa digunakan untuk bisa menghasilkan uang—diperbandingkan dengan laki-laki.
Karya sastra adalah sebuah pesan dari dunia tanpa rupa untuk menjadi bahan pemahaman dan kajian untuk kepentingan masyarakat. Citra sosial dan budaya sangatlah lekat di dalamnya. Lantas bagaimana masyarakat menyikapinya, terutama untuk menyerap elan vital sastra feminism.
Ciputat, 25 Oktober 2009
Pimpinan Redaksi Komunitas Mata Aksara
* Di presentasikan pada bulan Desember 2009, di Ruang 8 Jurnal Bogor.
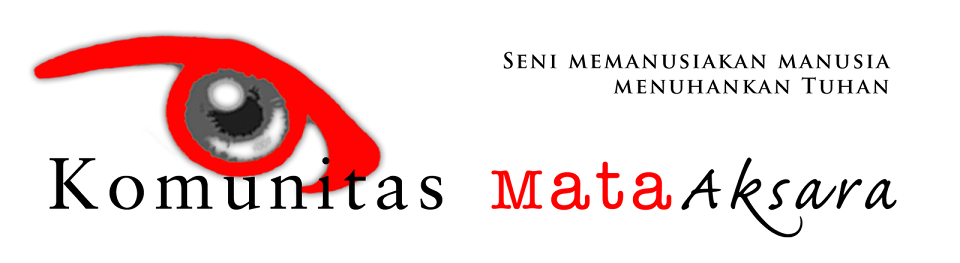
Tidak ada komentar:
Posting Komentar